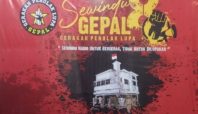JAKARTA — Pidato pembukaan delegasi Indonesia dalam Konferensi Iklim PBB ke-30 (COP 30) di Belem, Brasil, menuai sorotan tajam dari masyarakat sipil. Mewakili Presiden, Ketua Delegasi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan komitmen Indonesia memperkuat target iklim nasional dan menegaskan kesiapan bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai aksi iklim yang “inklusif dan ambisius.” Ia mengangkat capaian pemerintah mulai dari penurunan deforestasi hingga peningkatan bauran energi terbarukan serta komitmen menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Hashim dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meresmikan Paviliun Indonesia di COP 30, yang mengusung tema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon.” Di sana dijadwalkan lebih dari 50 sesi bicara melibatkan pejabat tinggi dan pimpinan korporat. Akan ada pula forum “seller meet buyer” – yang disebut pertama kali terjadi dalam sejarah Paviliun RI – untuk memfasilitasi transaksi karbon dengan potensi ekonomi sampai USD 7,7 miliar per tahun dan 90 juta ton unit karbon yang diklaim berkualitas.
Direktur Eksekutif WALHI Papua Maikel Peuki memandang langkah pimpinan delegasi RI itu sangat mengecewakan. “Fokus delegasi pada perdagangan karbon menjadikan misi Indonesia di COP 30 sangat transaksional, tanpa menunjukan komitmen kuat pada masyarakat adat dan masyarakat rentan lainnya. Ditambah lagi, Pemerintah mendorong solusi iklim yang pro-korporasi, seperti co-firing batubara, yang menambah beban ekologis,” kata Maikel saat menanggapi pembukaan COP 30 usai dialog publik “Suara Rakyat Indonesia untuk CoP-30.” yang diselenggarakan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI).
Terkait deforestasi, realitanya dalam setengah abad, antara 1950-2000, Indonesia kehilangan hampir 40 persen tutupan hutan—dari 162 juta hektare tersisa hanya 98 juta hektare. Deforestasi besar-besaran, terutama akibat ekspansi perkebunan sawit dan proyek pembangunan, memecah habitat dan mengancam kelangsungan spesies endemik. Data IUCN Red List mencatat 2.735 jenis flora dan fauna Indonesia kini terancam punah, lebih dari setengahnya merupakan tumbuhan.
 ">
">
Kerusakan semakin parah karena dari 2000 hingga 2012 saja Indonesia kehilangan lebih dari 6 juta hektare hutan primer—setara dengan hampir dua kali luas Pulau Bali—akibat konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Artinya, setiap tahun rata-rata 47.600 hektare hutan lenyap dari peta. Laju kehilangan ini terus berlanjut. Pada 2024, deforestasi hutan alami tercatat mencapai 261.575 hektare, meningkat 1,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari sektor penggunaan lahan dan kehutanan saja, emisi yang dihasilkan mencapai hampir setengah dari total emisi nasional.
Ironisnya, di tengah situasi krisis tersebut, pemerintah masih menetapkan target deforestasi hingga 10,47 juta hektare dalam periode 2021–2030. Target ini bahkan dipecah menjadi “deforestasi terencana” seluas 5,32 juta hektare dan “deforestasi tidak terencana” sebesar 5,15 juta hektare.
Menurut Maikel, dari perspektif Papua, sekitar 1,3 juta hektare hutan juga hilang antara 2001–2019 akibat sawit dan tambang. Dalam dialog publik ‘Suara Rakyat Indonesia untuk CoP-30” pada Senin (10/11) Maikel menyebutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke telah menyebabkan hilangnya 9.835 hektar hutan primer hingga Juni 2025. Industri kelapa sawit adalah pendorong terbesar kedua menghilangkan 3.577 hektar pada 2024.
Maikel menambahkan, banyaknya dukungan korporasi di Paviliun Indonesia menegaskan bahwa Pemerintah lebih berpihak kepada korporasi dan memberi izin industri ekstraktif tanpa memberi ruang hidup bagi masyarakat. “Perlindungan bagi masyarakat rentan, termasuk masyarakat pesisir dan nelayan masih kurang, terlihat dari lambatnya respons pemerintah terhadap berbagai bencana yang terjadi. Pemerintah juga harus melibatkan orang muda Papua dalam kebijakan perubahan iklim,” kata Maikel.
Diplomasi Hijau Tak Sejalan Realita
Selama dua pekan pelaksanaan COP 30, Paviliun Indonesia diklaim sebagai etalase diplomasi hijau dengan menampilkan inisiatif lintas sektor dari kehutanan, energi, industri, hingga pengelolaan limbah. Dalam sambutannya Hanif mengatakan bahwa misi Paviliun Indonesia adalah untuk menghubungkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat global melalui pasar karbon berintegritas tinggi.
Namun, di mata banyak organisasi lingkungan, pesan yang disampaikan delegasi Indonesia itu belum menunjukkan komitmen yang tegas dalam menjawab krisis iklim. Fokus besar pada perdagangan karbon dan proyek investasi tidak menyentuh akar persoalan pemanasan global yang kian memperburuk ketimpangan sosial dan ekologis di dalam negeri. Bagi kelompok masyarakat sipil, pidato itu lebih terdengar seperti promosi komoditas ekonomi hijau ketimbang komitmen iklim yang memberi solusi kepada rakyat.
Skema perdagangan karbon sendiri tidak otomatis menurunkan emisi, karena pada dasarnya skema ini memindahkan tanggung jawab pengurangan emisi dari satu pihak ke pihak lain tanpa memastikan adanya penurunan nyata di tingkat global. Mekanisme ini berisiko menjadi celah bagi korporasi besar untuk terus menghasilkan emisi, selama mereka mampu membeli kredit karbon dari wilayah lain yang lebih miskin. Alih-alih mengurangi polusi, pendekatan ini justru mempertahankan ketimpangan dan menunda perubahan untuk keluar dari ketergantungan pada energi fosil.
Yang terjadi di tapak adalah berbagai kerusakan akibat penambangan masif di seluruh nusantara. Ahmad Subhan Hafidz, Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung saat dialog publik ARUKI mengatakan, perusakan Bangka Belitung bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi berdampak pada keselamatan manusia. Contohnya lubang tambang yang diabaikan tanpa dilakukan perbaikan.
Ia menyebutkan bahwa di Kepulauan Bangka Belitung, deforestasi masif terjadi dalam kurun waktu enam tahun antara 2014-2020 yang menyebabkan hilangnya tropis seluas 460.000 hektar dari total luas daratan 1,6 juta hektar. Daratan Bangka Belitung dibebani izin ekstraktif hingga sekitar 70%, terutama pertambangan yang jumlahnya mencapai 1.007.372,66 Ha dan perkebunan sawit mencapai 170.000 Ha. Hal ini hanya menyisakan 197.255,2 hektare hutan.
“Terdapat hingga 12.607 kolong tambang yang tidak direklamasi. Kerusakan ini memicu bencana ekologis seperti banjir besar (2016), kekeringan panjang (2015), dan meningkatkan risiko gelombang ekstrim serta abrasi (42.245 hektar potensi bahaya). Antara 2021-2024, tercatat 26 kasus tenggelam di kolong, di mana 14 korban adalah anak-anak. Terumbu karang di Babel berkurang sekitar 64.514,99 hektare dalam kurun waktu dua tahun pada 2015-2017,” ungkap Hafidz.
Menurut Maria Un, perempuan disabilitas dan masyarakat adat asal Sulawesi Selatan, penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dan stigma. Mereka lebih rentan terhadap dampak krisis iklim. Ketika terjadi bencana iklim (longsor, banjir), penyandang disabilitas sulit beraktivitas. Mereka mengalami kelangkaan air bersih, penurunan hasil panen, dan kerusakan infrastruktur. Informasi bencana sulit diakses. Proses evakuasi dan pasca evakuasi sering terlupakan. “Bantuan yang diberikan tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik mereka. Tempat penampungan tidak aksesibel dan tidak aman,” katanya.
Gofur Kaboli, Nelayan asal Ternate mengatakan perlu jaminan dan perlindungan hak-hak nelayan kecil karena mereka adalah tulang punggung negeri yang paling merasakan dampak perubahan iklim. “Keputusan yang diambil dalam CoP-30 harus menjamin nelayan-nelayan kecil dari cuaca ekstrim,” kata Gofur.
Masyarakat sipil berharap, agenda adaptasi iklim di konferensi COP 30 berbasis hak dan indikatornya wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat adat yang tak terbatas pada hutan, tetapi juga hak tenurial, partisipasi inklusif, dan pengetahuan tradisional. Selain itu, upaya pendanaan iklim selayaknya tidak birokratis dan menghindari dominasi lembaga besar seperti bank multilateral, serta memberikan jalur langsung bagi komunitas.
Selain itu, masyarakat sipil juga ingin agar definisi transisi berkeadilan diperluas agar memasukkan hak atas ruang hidup, kedaulatan energi, dan model energi komunitas. Juga, memastikan kepentingan penyandang disabilitas dalam kebijakan iklim global serta mekanisme perlindungan bagi nelayan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.